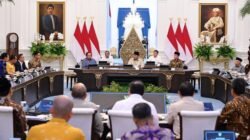MATRANEWS.id — “Saya sedih kalau melihat ada pemimpin terdahulu dikuyo-kuyo. Seperti Pak Jokowi. Jangan hanya melihat kelemahannya. Lihatlah prestasinya.”

Kalimat itu meluncur pelan, tapi sarat empati. Disampaikan di tengah riuh komentar publik yang sering kali lebih cepat menghakimi ketimbang memahami.
Tokoh itu menyinggung bagaimana ingatan kolektif bangsa sering terlalu pendek — terlalu tergesa menilai, terlalu cepat melupakan.
“Mana ada negara di dunia yang bisa menjaga inflasi 2,5% pasca pandemi?” lanjutnya.
Sebuah catatan yang kerap luput dari kesadaran publik. Setelah badai pandemi COVID-19 dan perang Rusia–Ukraina mengguncang rantai pasok global, hampir semua negara porak poranda.
Amerika Serikat sempat mencatat inflasi di atas 8% pada 2022. Eropa bahkan mendekati dua digit. Di Asia, banyak negara berkembang megap-megap dengan inflasi 5–7%.
Tapi Indonesia, entah bagaimana caranya, bertahan di angka 2,5%.
Dalam sejarah ekonomi modern, angka itu bukan sekadar statistik — melainkan cermin kendali politik dan intuisi kepemimpinan di tengah krisis.
“Ketika banyak mendesak Pak Jokowi untuk lockdown,” ucap sang narasumber lagi, “dengan intuisinya, beliau menolak. Dia memikirkan wong cilik, warung-warung kecil, ekonomi rakyat. Kalau lockdown, siapa yang makan? Dan ternyata keputusan itu benar. Dunia mengakuinya.”
Kisah itu bukan sekadar nostalgia politik. Ia menjadi fondasi moral yang menjelaskan mengapa Presiden Prabowo Subianto kini mengambil sikap yang positif terhadap berbagai warisan Jokowi — termasuk proyek Whoosh dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pewaris dan Penanggungjawab
Prabowo tidak sedang mencari legitimasi dari masa lalu. Ia justru meneguhkan posisi dirinya sebagai penanggungjawab atas masa depan.
“Banyak suara miring,” kata narasumber tadi dengan nada sedikit geram, “katanya, enak saja dia bilang bertanggung jawab soal Whoosh, memangnya mau bayar pakai uang pribadi? Uang rakyat juga yang dipakai!”
Ia terdiam sejenak, lalu menukas pendek:
“Betapa picik dan naifnya pemikiran seperti itu. Kucluk!”
Dalam satu kata itu, terkandung sindiran terhadap sikap sempit: mengukur kepemimpinan hanya lewat angka kas negara, bukan nilai keberlanjutan. Siapa pun presiden Indonesia, dari era Soekarno hingga kini, selalu bekerja dengan uang rakyat. Tapi tidak semua mampu mengonversi uang rakyat menjadi nilai peradaban.
Whoosh dan “Investasi Peradaban”
Whoosh — kereta cepat pertama di Asia Tenggara — bukan sekadar proyek transportasi. Ia simbol peradaban.
“Bukan soal bayar utang,” ujar narasumber itu. “Ini investasi peradaban. Lompatan menuju level kehidupan baru. Peningkatan martabat bangsa.”
Dalam kacamata itu, Prabowo tampak berusaha melanjutkan logika kemajuan Jokowi, tapi dengan skala lebih besar: mengubah proyek infrastruktur menjadi basis transformasi nasional. Dari beton menjadi visi. Dari jalur cepat menjadi arah masa depan.
“Semua itu disebut visi,” ujarnya pelan. “Dan ternyata bukan cuma Jokowi, Prabowo juga memilikinya.”
Mereka yang Jalan di Tempat
Prabowo, kini di kursi nomor satu republik ini, tampak mulai membangun narasi tentang kesinambungan dan tanggung jawab sejarah.
Dalam setiap ucapannya tentang Whoosh, IKN, atau ketahanan pangan, ada benang merah: tidak ada pembangunan yang lahir dari kebencian terhadap masa lalu.
Sementara itu, suara-suara sumbang terus datang — dari mereka yang menatap masa depan dengan cermin pecah di tangan.
“Ketika pikiran Prabowo sudah beberapa langkah ke depan,” kata sang narasumber menutup pembicaraan, “para pemilik suara sumbang itu masih jalan di tempat. Saya jadi makin paham, itu sebabnya Prabowo yang jadi presiden — bukan mereka.”
Di antara retorika dan realitas, cerita ini menyingkap satu hal yang kerap terlewat: politik yang matang tidak hanya soal siapa yang berkuasa, tapi siapa yang mampu menanggung warisan.
Dan di situ, sejarah tampaknya mulai menulis bab barunya — dengan Prabowo di halamannya.