MATRANEWS.id — Enam tahun lalu, ketika palu dipalu dan Perjanjian Paris disetujui, para perunding yang berkumpul di kompleks konferensi besar di pinggiran Paris meledak dengan tepuk tangan dan meninggalkan kota dengan rasa optimis.
Perayaan pun terjadi di bar-bar, di seluruh kota untuk ribuan orang yang telah melakukan perjalanan ke Paris untuk mendorong kesepakatan.
Suasana berbeda di Penutupan COP26
Bagaimana dengan situasi COP26 ini?
Sangat berbeda. Pada Sabtu (12/11), COP26 di Glasgow ditutup dengan semangat yang jauh berbeda.
COP26 menghasilkan tiga naskah penting, yaitu naskah hasil COP26, pembaruan perjanjian Protokol Kyoto 1997, dan pembaruan Perjanjian Paris 2015.
Hasil COP26 menitikberatkan pada lima poin mendasar.
Lima poin tersebut antara lain ini
Pemangkasan emisi karbon, komitmen penurunan penggunaan batu bara secara bertahap, adaptasi finansial iklim, adaptasi terhadap dampak kehilangan dan kerusakan akibat iklim, dan pembaruan Perjanjian Paris mengenai target pengendalian kenaikan suhu sebesar 1,5°C.
Kesepakatan baru ini mengawali langkah besar ke depan dalam diskusi iklim internasional—meskipun hanya sedikit delegasi yang siap merayakannya secara terbuka.
Dalam pernyataan demi pernyataan yang dilontarkan selama sesi penutupan, negosiator dari negara-negara di seluruh dunia menyatakan bahwa, mereka menerima hasil COP26 dalam “semangat kompromi”.
Catatan pinggirnya adalah, semangat “kompromi sambil” menyesali bahwa kesepakatan itu tidak berjalan cukup jauh.
Beragam reaksi dari negara-negara peserta
Kesimpulan COP26 ternyata membawa pesan dan reaksi yang beragam.
Di satu sisi, negara-negara peserta secara umum telah memberi isyarat bahwa bahan bakar fosil bukanlah masa depan.
Di sisi lain, bagi negara berkembang dan negara miskin, melaksanakan pembangunan dan mengentaskan kemiskinan.
Sekaligus melakukan transisi ke energi terbarukan secara bersamaan bukanlah hal yang mudah dan murah.
Hal ini, tentu saja, akan memengaruhi masyarakat sipil dan masyarakat adat di negara-negara tersebut.
Syalomitha Hukom, seorang akademisi lulusan The University of Auckland dalam tesisnya yang berjudul “Climate Change: Impact on the Efficacy of Indigenous Knowledge” menyatakan, masyarakat adat adalah pihak yang paling sensitif dan mengalami dampak dari perubahan iklim.
Padahal, dalam praktek kehidupannya, mereka hanya menghasilkan sangat sedikit emisi karbon dikarenakan gaya hidup tradisional yang mereka jalankan.
Jadi, tidaklah adil jika masyarakat adat dari negara miskin dan berkembang juga harus ikut menanggung beban akibat fenomena perubahan iklim yang dimulai sejak revolusi industri oleh negara barat pada abad ke-18.
Komitmen Negara Maju
Pada hari-hari terakhir pembicaraan di Glasgow, negosiasi sebagian besar berpusat pada dorongan bagi negara-negara kaya, untuk menyediakan dana yang memadai bagi negara-negara miskin.
Inisiatif tersebut bertujuan agar semua negara bekerja sama untuk dapat beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.
Seperti membantu membayar kerusakan yang tak terhindarkan dan menyebabkan kerugian finansial.
Misalnya, negosiator dari AS, Inggris, Jerman, Prancis, dan Uni Eropa mengumumkan bahwa, mereka sedang mengerjakan kesepakatan senilai $8,5 miliar.
Dengan Afrika Selatan untuk membantu negara tersebut beralih dari batu bara menuju energi terbarukan.
Contoh kemitraan di atas dapat dijadikan referensi model bantuan finansial bagi negara maju lainnya.
Hal ini, dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab dari ‘dosa historis’ yang mereka lakukan berabad-abad lalu.
Memang benar, bahwa para perunding yang berkumpul di Glasgow tidak memiliki kekuatan langsung untuk campur tangan di lapangan di negara lain.
Akan tetapi, secara kolektif menentukan arah tidak ada salahnya.
****

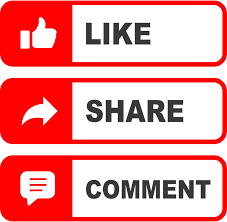

BACA JUGA: majalah eksekutif edisi November 2021






