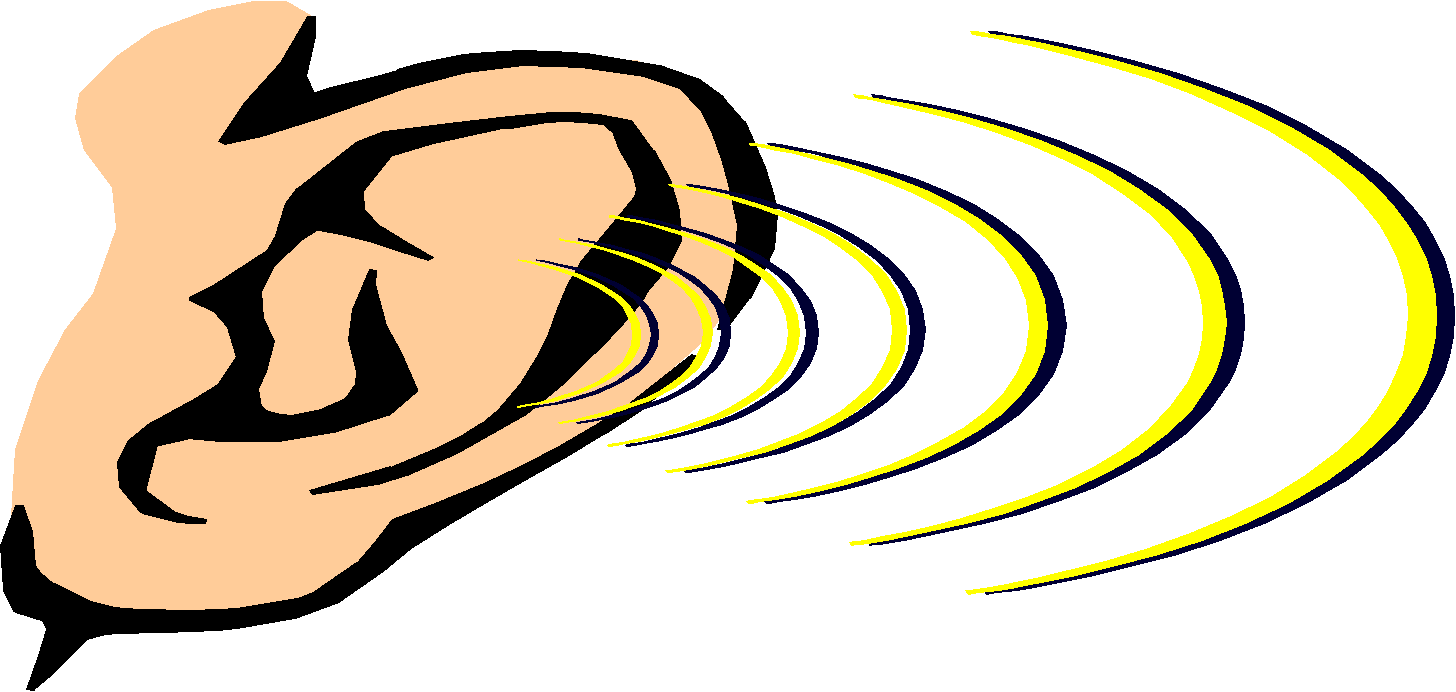
JIKA SAJA TELINGA HADIR DAN BERARTI BUKAN SEBAGAI ALAT pendengar saja, barangkali dunia bisa jadi tempat serasa surga. Kecurigaan tidak lahir. Dan pertentangan yang bisa menyebabkan terjadinya pertengkaran tidak bakal terjadi.
Memang, tidak salah jika orang bilang “mendengar dengan telinga, menyerap dengan rasa.” Tapi, “meresapi dengan telinga” tak keliru pula.
Ada permainan yang hingga kini masih sering dilakukan oleh guru-guru taman kanak-kanak. Jika hendak menguji lima atau enam anak. Susun sebuah kalimat terdiri atas lima atau enam kata.
Beri tahukan kepada anak di jejer pertama, diam-diam. Lalu suruh anak itu membisikkan ke telinga anak yang kedua di sebelahnya. Anak yang kedua juga harus membisikkan kalimat itu ke telinga anak yang ketiga.
Anak ketiga kepada yang keempat, begitu seterusnya. Kemudian, minta anak yang terakhir mengucapkan keras-keras apa isi kalimat yang dibisikkan secara beruntun itu.
Hasilnya?
Banyak guru yang kecewa.
Mengapa?
Lantaran yang diucapkan oleh anak terakhir sering tidak sama dengan kalimat awal. Malah kadang jauh sekali melencengnya.
Tak jarang bisa melahirkan arti yang bertentangan. Padahal, lima atau enam anak itu sudah diperiksa kesehatan telinganya. Dan semua ada dalam kondisi prima.
Kemudian, ketika si guru menyatakan kalimat itu salah, terjadi keadaan saling menyalahkan. Si anak pertama menyalahkan anak yang kedua. Anak terakhir menyalahkan anak sebelumnya, dan seterusnya.
Itulah sifat dan gosip, kata teman saya.
Semili bisa jadi seinci. Sedikit bisa jadi sebukit. Di tengah jalan akan semakin berkembang.
Tapi, mengapa kalimat yang dibisikkan itu bisa berkurang, atau malah melenceng?
Saya ingat, ada yang pernah mengupas hal. Pertama, lantaran kalimat itu dibisik-bisikkan. Kedua, karena ketika sedang mendengar, si anak tidak hanya mendengar tapi fantasinya juga ikut berkembang.
Ketiga, keadaan terburu-buru. Bukankah si anak diharuskan segera membisikkan kalimat itu ke telinga lain? Dalam hal ini, yang diingat si anak bisanya cuma keburu-burunya dan bukan apa yang telah didengarnya.
Akurasi tergeser tempatnya.
Tampaknya, hubungan antara kesimpulan pertama, kedua, dan ketiga sangatlah erat. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, transparansi menjadi sangat penting.
Keterbukaan mampu menjelaskan seluruh persoalan yang masih di bawah permukaan. Berbagai peraturan atau si anu menang tender, misalnya, jika tak dijelaskan latar belakangnya tentu akan menimbulkan bisik-bisik yang tak sedap.
Ini bisa rnerugikan. Sudah dijelaskan panjang lebar pun terkadang masih menimbulkan salah pengertian, apalagi jika hanya dibisik-bisikkan. Atau dipendam.
Jika daya ingat kurang, atau telinga tak sudi mendengar apa yang seharusnya di dengar, biasanya yang mengambil alih peran adalah daya fantasi.
Ini celaka. Karena daya fantasi sangat personal. Jadi, yang kelak terucap bukan maunya kenyataan, melainkan maunya yang ingin dibayangkan dan orang yang mendengar itu. Kan bisa kacau?
Bukankah gosip juga begitu?
Kata teman saya lagi. Sebagai anggota badan, telinga juga punya peran penting.
Dan ternyata bisa mempengaruhi anggota badan lain pula. Contoh, jika telinga tak mampu mendengar, mulut juga tak akan mampu mengucapkan kata-kata.
Maka, terbentanglah sebuah “dunia yang senyap,” seperti yang pernah diungkapkan dengan sangat puitis oleh sebuah film Jepang.
Telinga adalah jembatan menuju rasa. Ia bukan dipakai hanya untuk mendengar, tapi wajib dimanfaatkan untuk meresapi apa yang didengar.
Merekam dengan benar. Lalu menyampaikan ke dalam hati, agar berani menyimpulkan kebenaran itu. Dan kata-kata, kemudian melantunkannya. Alangkah indah dunia jika begitu keadaannya.


baca juga: majalahmatra.com — edisi cetak — klik ini

 www.majalahmatra.com
www.majalahmatra.com









